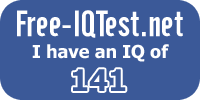PENDAHULUAN
Artroskopi sendi lutut menimbulkan sinyal nyeri aferen yang memulai perubahan pada sistem saraf sehingga memperkuat dan memperpanjang nyeri pascaoperasi. Pencegahan nyeri ini dilakukan dengan pemberian obat analgesik sebelum timbul rangsangan nyeri. Akhir-akhir ini, regimen obat kombinasi telah direkomendasikan dalam manajemen nyeri pascaoperasi artroskopi sendi lutut. Dalam banyak penelitian, bupivakain dan morfin yang diberikan secara intraartikular adalah obat analgesik yang efektif pascaoperasi artroskopi sendi lutut. Ketorolak, kortikosteroid, dan klonidin juga berperan mengurangi nyeri pascaoperasi artroskopi sendi lutut. Obat-obat anti inflamasi nonsteroid memegang peranan penting dalam manajemen nyeri pascaoperasi ortopedik, termasuk obat yang spesifik terhadap enzim siklooksigenase-2 yang lebih aman jika digunakan.
Teknik kombinasi obat analgesik yang diberikan sebelum timbul rangsangan nyeri, dapat digunakan dalam manajemen nyeri pascaoperasi artroskopi sendi lutut. Artroskopi sendi lutut merupakan prosedur yang rutin dilakukan untuk pasien rawat jalan. Umumnya, obat analgesik oral diberikan untuk mengatasi nyeri pascaoperasi, tetapi sering tidak efektif.1 Nyeri pascaoperasi yang tidak teratasi, dapat memperpanjang masa rawat inap pasien, menunda program rehabilitasi, memperlambat penyembuhan, serta memberdayakan lebih banyak tenaga kesehatan.1 Akhir-akhir ini, banyak teknik yang tersedia untuk mengatasi nyeri pascaoperasi artroskopi sendi lutut, termasuk penggunaan obat golongan opioid (menimbulkan efek analgesik secara perifer maupun sentral), obat anestesi lokal, obat antiradang nonsteroid, kortikosteroid, klonidin, serta krioterapi (lihat gambar 1). Makalah ini berisi pembahasan mengenai peran obat analgesia kombinasi dalam pencegahan nyeri pascaoperasi artroskopi sendi lutut.
Gambar 1. Lokasi target obat analgetik sepanjang jalur nyeri dari sistem saraf perifer ke susunan saraf pusat.
PEMBAHASAN
Fisiologi nyeri
Prosedur operasi menimbulkan sinyal nyeri dan respon inflamasi sekunder yang mengakibatkan nyeri pascaoperasi. Sinyal-sinyal ini memulai perubahan di sistem saraf perifer dan susunan saraf pusat, yang akhirnya menguatkan dan memperlama nyeri pascaoperasi.2 Sensitisasi sistem saraf perifer (penurunan ambang nyeri nosiseptor aferen) diakibatkan oleh peradangan di tempat timbulnya luka operasi.3
Sensitisasi susunan saraf pusat (perangsangan neuron spinal), disebabkan oleh paparan menetap terhadap input aferen nosiseptif dari neuron-neuron perifer.4 Sensitisasi saraf perifer dan susunan saraf pusat, mengakibatkan keadaan hipersensitivitas setelah dilakukannya operasi. Hal ini menurunkan ambang nyeri, baik pada tempat timbulnya luka (hiperalgesia primer), maupun daerah sekitarnya (hiperalgesia sekunder).5 (lihat gambar 2).
Gambar 2. Luka operasi mengakibatkan pelepasan mediator-mediator inflamasi pada tempat luka, mengakibatkan penurunan ambang nyeri pada lokasi operasi( hiperalgesia primer) maupun daerah sekitarnya (hiperalgesia sekunder). Sensitisasi susunan saraf pusat (perangsangan neuron spinal), disebabkan oleh paparan menetap terhadap input aferen nosiseptif dari neuron-neuron perifer.
Akhir-akhir ini, kemajuan pemahaman mengenai mekanisme timbulnya nyeri menghasilkan konsep pemberian obat analgesik sebelum timbul rangsangan nyeri. Tujuannya adalah untuk mencegah sensitisasi susunan saraf pusat yang dapat memperkuat nyeri pascaoperasi.5 Konsep ini berdasarkan penelitian pada hewan yang mengungkap bahwa obat anestesi lokal atau opioid dapat mencegah gejala ikutan fisiologis maupun perilaku yang timbul setelah rangsangan nyeri dalam waktu singkat.6, 7, 8 Sebaliknya, obat-obat ini kurang efektif jika diberikan setelah terjadinya rangsangan terhadap susunan saraf pusat. Namun, hasil pada penelitian terhadap manusia lebih kontroversial.9
Pengurangan nyeri yang optimal susah didapatkan dengan satu jenis obat atau satu metode.10 Akhir-akhir ini direkomendasikan penggunaan regimen obat analgesik kombinasi (multimodal) yang bekerja melalui mekanisme atau lokasi target yang berbeda. Regimen obat analgesik kombinasi saling bekerja secara sinergis sehingga dosis dapat diperkecil dan efek samping dapat dikurangi. 10 Dewasa ini, banyak teknik analgesia yang digunakan untuk menghambat transmisi nosiseptif postoperasi artroskopi sendi lutut. Pada tingkat susunan saraf perifer, dapat digunakan obat anti inflamasi nonsteroid, kortikosteroid, opioid, atau krioterapi. Obat anestesi lokal menghambat transmisi saraf pada lokasi timbulnya luka, sedangkan obat opioid oral bekerja pada tingkat susunan saraf pusat. (lihat gambar 1).
Tujuan utama dari manajemen nyeri terkini adalah untuk mengurangi nyeri pada tingkat sentral maupun perifer dengan penggunaan obat analgesik yang diberikan sebelum timbul rasa nyeri. Strategi ini diikuti dengan program rehabilitasi medik sehingga hasil penyembuhan lebih optimal.
Artroskopi sendi lutut
Artroskopi sendi lutut mencegah insisi yang luas, serta mengurangi morbiditas dibandingkan dengan prosedur operasi terbuka, tetapi tidak mengurangi rasa nyeri.11 Sebagian besar struktur dalam sendi lutut (termasuk jaringan sendi, bantalan lemak anterior, dan kapsula sendi) memiliki ujung saraf bebas yang dapat bereaksi hebat terhadap rangsang nyeri.12 Prosedur artroskopi dapat menimbulkan nyeri dan bengkak yang dapat menunda program rehabilitasi medik, serta menunda pasien untuk beraktivitas setelah lebih dari dua minggu setelah operasi.13, 14 Pasien yang tidak dapat mengikuti program rehabilitasi secara lengkap, berisiko lebih tinggi untuk mengidap komplikasi pascaoperasi (antara lain penurunan kekuatan, kekakuan lutut, dan nyeri lutut anterior). 13, 15, 16 Oleh karena itu, manajemen nyeri yang agresif pada saat awal pascaoperasi, sangatlah penting dan mempercepat pemulihan setelah dilakukan artroskopi.17
Bupivakain intraartikular
Anestesi lokal intraartikular sering digunakan untuk manajemen nyeri perioperasi. Bupivakain merupakan obat anestesi lokal yang memiliki gugus amin dan sering digunakan karena memiliki durasi kerja yang panjang.18 Kadar puncaknya dalam serum tercapai dalam waktu tiga puluh sampai enam puluh menit setelah disuntikkan. Bupivakain aman jika disuntikkan kurang dari sama dengan 150 miligram ke dalam sendi lutut.19 Bupivakain intraartikular yang diberikan dengan dosis kurang dari sama dengan 0,5 % tidaklah berbahaya bagi kartilago sendi.20
Efisiensi analgesia dari bupivakain yang disuntikkan secara intraartikular, masih kontroversial. Beberapa penelitian telah gagal membuktikan adanya efek analgesia yang baik dari bupivakain yang diberikan secara intraartikular 21,22. Sedangkan penelitian yang lain membuktikan adanya beberapa manfaat dari pemberian bupivakain intraartikular. 23,24,25 Sayangnya penelitian-penelitian ini memiliki kelemahan dalam desain penelitian, pengumpulan data, dan pelaporan data. Selain itu, juga terdapat variasi volume dan konsentrasi dari bupivakain yang disuntikkan secara intraartikular. Namun, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap nyeri postoperasi, antara lain penggunaan obat anti inflamasi nonsteroid, opioid, turniket, epinefrin, serta anestesi infiltrasi dengan lidokain maupun bupivakain.
Dosis bupivakain merupakan faktor yang penting. Smith dkk. menyatakan bahwa dosis 0,25 % mengakibatkan kurangnya efek analgesik bupivakain intraartikular pada penelitian-penelitian sebelumnya. 25 Oleh karena itu, Smith dkk. memberikan bupivakain 0,5 % sebanyak 30 ml (150 mg) kepada 97 pasien yang dibius umum ketika menjalani operasi artroskopik. Pasien dibagi menjadi 2 golongan secara acak, sebagian mendapat bupivakain intraartikular dan yang lainnya mendapat larutan salin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang mendapat bupivakain 0,5 % lebih sedikit membutuhkan narkotika pascaoperasi dibandingkan kelompok yang mendapat larutan salin. Bahkan, pasien yang mendapat bupivakain 0,5 % lebih cepat pulih.
Faktor visual analog pain scores yang rendah (kurang dari 3,3 cm) juga mengakibatkan kurangnya efek analgesik bupivakain intraartikular pada penelitian-penelitian sebelumnya. Banyak prosedur dalam penetian-penelitian tersebut merupakan tindakan artroskopi diagnostik yang hanya membutuhkan sedikit obat analgesik postoperasi. Penelitian Geutjens dan Hambidge menyatakan bahwa kelompok kontrol yang hanya diberikan larutan salin,ternyata tidak membutuhkan obat analgesik 10 jam postoperasi.24 Faktor lain yang juga tidak diperhatikan adalah hemarthrosis postoperasi yang bisa menambah rasa nyeri dan mengurangi konsentrasi bupivakain dalam sendi lutut.
Jadi, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa bupivakain intraartikular merupakan obat analgesik yang efektif dalam manajemen nyeri postoperasi artroskopi sendi lutut. Akan tetapi, perlu penelitian dengan desain yang lebih baik untuk mendapat kesimpulan akhir.
Morfin intraartikular
Bupivakain intraartikular memiliki efek analgesia postoperasi yang efektif, tetapi hanya bertahan 2 sampai 4 jam.23,24 Pasien yang pulih dari operasi artroskopi sendi lutut, masih membutuhkan obat analgesia tambahan sebelum dan sesudah pulang dari rumah sakit. Obat analgetik golongan narkotika adalah yang biasanya dipilih, tetapi memiliki efek samping seperti depresi napas, sedasi, pruritus, mual, serta muntah. Hal ini bahkan dapat memperpanjang masa rawat inap pasien, meningkatkan morbiditas, serta meningkatkan risiko ketika pasien sudah pulang ke rumah. Obat golongan opioid yang diberikan secara oral, tidak dapat diabsorpsi karena timbulnya mual, muntah, serta ileus yang terjadi setelah operasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa reseptor opioid yang berada di jaringan perifer, dapat mencegah atau mengurangi nyeri pascaoperasi.
Telah lama diketahui bahwa terdapat reseptor opioid di susunan saraf pusat, tetapi penemuan terbaru menyatakan bahwa reseptor opioid juga terdapat di ujung saraf bebas.26 Hal ini telah dianalisis secara imunohistokimia dari spesimen biopsi jaringan sendi meradang, juga telah dibuktikan dengan adanya pengikatan nalokson ke reseptor opioid di lutut.27 Ketiga reseptor opioid (mu, delta, dan kappa) terbukti ada pada saraf-saraf perifer, serta berperan dalam mediasi antinyeri di perifer.28 Reseptor-reseptor ini disintesis di dalam badan sel neuron sensorik primer yang terletak di radix dorsalis ganglion, serta disalurkan ke arah distal oleh akson.29
Terdapat teori bahwa opioid yang diberikan secara lokal dapat memberikan efek analgesia pada jaringan yang mengalami inflamasi dan bukan pada jaringan yang sehat.30 Teori pertama adalah bahwa inflamasi menginduksi daerah di sekitar saraf sehingga memudahkan akses opioid mengikat reseptor yang terdapat di neuron. Teori kedua adalah bahwa reseptor opioid yang sebelumnya tidak aktif, dapat menjadi aktif oleh proses inflamasi. 31
Mekanisme efek antinyeri opioid di susunan saraf perifer pada jaringan yang mengalami inflamasi, belum dapat secara tepat dijelaskan. Namun, hipotesis menyatakan bahwa terdapat efek antiinlamasi selain efek analgesik.27 Efek analgesik terjadi karena morfin mengurangi perangsangan ujung serat saraf C terhadap nyeri. Hal ini mengurangi pengiriman sinyal nyeri ke susunan saraf pusat. Opioid juga memiliki efek antiinflamasi yang bekerja secara langsung di jaringan perifer. Hal ini terjadi karena pengikatan reseptor opioid di perifer, mengurangi pelepasan neuropeptida hasil dari inflamasi, seperti substansi P.30
Stein dkk, telah membuktikan bahwa pemberian morfin intraartikular dalam dosis kecil pada manusia, menimbulkan efek analgesik yang lama.32 Efek lokal morfin dibuktikan dengan rendahnya kandungan morfin dan metabolitnya di plasma darah. Efek lokal morfin juga dibuktikan dengan penelitian yang memberikan dosis rendah morfin melalui jalur sistemik, tetapi tidak memberikan efek analgesia yang berarti.33, 34, 35 Akhirnya, Stein dkk. membuktikan bahwa efek analgesik dari morfin yang diberikan secara intraartikular, dapat dihambat oleh pemberian nalokson intraartikular. Hal ini mengkonfirmasikan adanya efek lokal dari opioid.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa morfin yang diberikan secara intra artikular juga mengurangi skor nyeri setelah 8 sampai 12 jam penyuntikan.36, 37, 38 Hal ini menyebabkan para peneliti mengkombinasi bupivakain intraartikular dan morfin intraartikular sebagai obat analgesik pascaoperasi.
Banyak peneliti gagal membandingkan efek analgesik morfin intraartikular dengan larutan salin ataupun bupivakain intraartikular. Hal ini terjadi karena penggunaan opioid sistemik, obat antiinflamasi nonsteroid, atau obat anestesi regional yang semuanya dapat mengurangi inflamasi akibat pembedahan sehingga mengurangi pengikatan morfin secara intraartikular.39, 40 ,41
Anestesi epidural juga dapat mengubah efek morfin yang diberikan secara intraartikular. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena anestesi epidural menghambat respon neuroendokrin terhadap luka operasi, serta mengurangi pelepasan mediator inflamasi.42 Kedua, anestesi epidural dapat mencegah dan memperlama efek analgesik postoperasi.2, 43, 44 Ada satu penelitian yang mengungkap bahwa anestesi epidural memiliki efek analgesik yang lama, yaitu selama 48 jam postoperasi.45
Faktor lain yang mempengaruhi efek analgesik morfin intraartikular adalah pelepasan turniket. Makin lama pelepasan turniket setelah penyuntikan morfin intraartikular, maka pengikatan terhadap reseptor opioid akan meningkat sehingga efek analgesik morfin juga meningkat. Whitford dkk. menyatakan bahwa pemasangan turniket selama 10 menit setelah penyuntikan morfin intraartikular, akan meningkatkan efek analgesik morfin, serta mengurangi pemakaian obat analgesik tambahan.46
Walau morfin intraartikular biasanya diberikan setelah prosedur artroskopi dilakukan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa pemberian postoperasi juga memberikan manfaat.47, 48
Kesimpulannya, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pemberian morfin secara intraartikular memberikan efek analgesik yang lama. Efek samping yang terjadi pada pemberian opioid secara sistemik, tidak terjadi pada pemberian morfin secara intraartikular. Peradangan di dalam jaringan sendi akan meningkatkan efek analgesik dari morfin, tetapi mekanisme kerjanya belum diketahui. Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid beserta obat anestesi spinal atau epidural, akan mengaburkan efek analgesik morfin. Hasil penelitian mendukung penggunaan morfin secara intraartikular untuk mengatasi nyeri pascaoperasi artroskopi sendi lutut.
Ketorolak intraartikular
Banyak peneliti yang menyelidiki efek analgesik dari pemberian obat antiinflamasi nonsteroid secara intraartikular. Salah satunya adalah ketorolak yang terbukti efektif mengurangi nyeri pasca artroskopi jika diberikan secara parenteral.49 Reuben dan Connelly membandingkan efek analgesik antara ketorolak yang diberikan secara parenteral dengan intraartikular. Hasilnya ternyata pemberian ketorolak intraartikular memiliki durasi analgesik yang jauh lebih lama. 50 Namun, penelitian ini mengundang kontroversi berkenaan dengan keamanan penggunaan ketorolak intraartikular.51, 52 Walau belum ada penelitian pada manusia, namun penelitian secara in vitro menunjukkan bahwa pemberian ketorolak secara intraartikular, tidak merusak kartilago tulang sapi. 53 Sebaliknya, ketorolak melindungi kartilago sendi dengan menghambat pelepasan sitokin, termasuk interleukin-1, yang memegang peranan penting dalam kerusakan kartilago. Selain itu, juga ada kewaspadaan terhadap kandungan alkohol dalam ketorolak yang dapat merusak kartilago sendi (10 % dari berat volume).51 Namun, dalam penelitian-penelitiaan tersebut, ketorolak diencerkan dalam 30 ml bupivakain 0,25 % sehingga kandungan alkoholnya hanya 0,7 % dari berat volume. Kandungan alkohol ini lebih rendah daripada kandungan alkohol 0,9 % dalam larutan asetonida triamsinolon yang telah disetujui FDA (Food and Drug Administration) untuk penyuntikan intraartikular.
Connelly dan Reuben mendesain suatu penelitian untuk membandingkan efek analgesia ketorolak dengan morfin, serta menentukan apakah kombinasi kedua obat ini memberikan hasil efek analgesik yang lebih baik.54 Delapan puluh pasien yang menjalani meniskektomi dengan artroskopi, secara acak diberikan ketorolak dan morfin yang diberikan secara intravena maupun intraartikular. Hasilnya ternyata morfin dan ketorolak lebih baik tidak dikombinasi jika diberikan secara intraartikular (efek analgesiknya dapat bertahan selama 13 jam). Sedangkan kombinasi morfin dan ketorolak intraartikular tidak menambah efek analgesik, serta tidak memperlama efek analgesik. Hipotesis yang dapat menjelaskan hal ini adalah karena ketorolak mengurangi proses peradangan di dalam jaringan sendi sehingga menghambat pengikatan reseptor opioid. Hipotesis lain menyatakan bahwa morfin atau ketorolak yang dicampur dengan pemberian bupivakain intraartikular, memiliki efek analgesia maksimal yang tidak bisa lagi ditambah.
Kortikosteroid intraartikular
Wang dkk. membuktikan bahwa suntikan asetonida triamsinolon dalam larutan salin ke dalam sendi lutut, akan mengurangi skor nyeri dan efek samping opioid. 55 Namun, nyeri berkurang setelah 6 jam penyuntikan kortikosteroid intraartikular, serta menetap selama 24 jam. Rasmussen dkk. membandingkan kombinasi bupivakain, morfin, dan metilprednisolon yang diberikan secara intraartikular dengan kombinasi bupivakain, morfin, dan larutan salin. Hasilnya menunjukkan bahwa kombinasi 150 mg bupivakain dan 4 mg morfin, akan mengurangi nyeri serta mempercepat pemulihan pasien. Penambahan 40 mg metilprednisolon akan lebih mengurangi nyeri, mengurangi pembengkakan sendi, mempercepat pemulihan pasien, meningkatkan fungsi otot, serta mengurangi respon inflamasi. Oleh karena itu, Rasmussen merekomendasikan pemberian kombinasi bupivakain, morfin, dan metilprednisolon untuk pasien yang menjalani meniskektomi dengan artroskopi.17
Akan tetapi, kortikosteroid memiliki efek samping meningkatkan risiko infeksi, kerusakan kartilago, penyembuhan luka tidak sempurna, dan efek samping sistemik. Namun, dalam penelitian ternyata efek sampingnya sedikit sekali.55, 56, 57
Klonidin intraartikular
Banyak penelitian yang mengungkap adanya efek analgesik pada klonidin yang diberikan secara intraartikular pascaoperasi artroskopi sendi lutut. 58, 59, 60 Klonidin adalah suatu a-2 agonis yang dapat digunakan sebagai obat anestesi lokal dengan durasi efek analgesik yang panjang karena memblok konduksi serat saraf A d maupun C. 61,62 Selain itu, klonidin juga dapat melepas zat yang menyerupai enkefalin sehingga menimbulkan efek analgesia di jaringan perifer. 63 Gentili dkk. membandingkan efek 150 mg klonidin yang diberikan secara intraartikular dan subkutan dengan larutan salin atau 1 mg morfin intraartikular pada 40 pasien yang menjalani artroskopi sendi lutut. Pasien yang mendapat klonidin intraartikular ternyata merasakan efek analgesia yang lebih lama (533 ± 488 menit) dibandingkan dengan pasien yang hanya mendapat larutan salin (70 ± 30 menit) atau klonidin subkutan (132 ± 90 menit). Durasi efek analgesia dari klonidin intraartikular ternyata hampir sama dengan penyuntikan morfin intraartikular (300 ± 419 menit). Oleh karena penyuntikan klonidin secara subkutan tidak menghasilkan efek analgesik yang efektif, maka Gentili dkk. menyatakan bahwa klonidin memiliki efek analgesik terhadap jaringan perifer.58
Oleh karena klonidin dapat meningkatkan blok saraf perifer dari obat anestesi lokal, maka Reuben dan Connelly meneliti efek analgesik 75 mg bupivakain intraartikular dan klonidin (1 ug/kg BB) pada pasien yang menjalani meniskektomi dengan artroskopi. Ternyata kelompok yang mendapat kombinasi bupivakain dan klonidin intraartikular, lebih kurang membutuhkan obat analgesik pascaoperasi, serta durasi efek analgesiknya juga lebih lama.60
Joshi dkk. berusaha untuk menemukan adanya tambahan efek analgesik pada klonidin intraartikular yang dikombinasi dengan morfin intraartikular. Mereka meneliti 60 pasien yang menjalani meniskektomi dengan artroskopi, serta memakai anestesi lokal. Kombinasi kedua obat tersebut menunjukkan peningkatan durasi efek analgesik (1050 ± 227 menit) dibandingkan dengan pemberian klonidin saja (640 ± 113 minutes) atau morfin saja (715 ± 106 minutes).64
KESIMPULAN
Ketorolak dan kortikosteroid bekerja sebagai obat analgesik poten yang mengurangi respon inflamasi akibat prosedur artroskopi. Sedangkan klonidin intraartikular akan meningkatkan efek morfin dan bupivakain intraartikular. Pengurangan nyeri dan bengkak pada sendi, akan mempercepat pemulihan kekuatan otot, serta mempercepat pemulihan pasien. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa obat antiinflamasi nonsteroid, kortikosteroid, serta klonidin memiliki peranan penting sebagai regimen obat analgesik untuk pasien yang menjalani prosedur artroskopi sendi lutut. Akan tetapi, masih diperlukan penelitian dalam skala yang lebih besar untuk meneliti efek samping dan efek dari regimen ini.
DAFTAR PUSTAKA
1. United States Acute Pain Management Guideline Panel: Acute Pain Management: Operative or Medical Procedures and Trauma. Pub. no. 92-0032. Rockville, Maryland, United States Department of Health and Human Services, Public Health Service Agency for Health Care Policy and Research, 1992.
2. Woolf, C. J, and Chong, M. S.: Preemptive analgesia - treating postoperative pain by preventing the establishment of central sensitization. Anesth. and Analg., 77: 362-379, 1993.
3. Raja, S. N.; Meyer, R. A.; and Campbell, J. N.: Peripheral mechanisms of somatic pain. Anesthesiology, 68: 571-590, 1988.
4. Woolf, C. J.: Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity. Nature,, 306: 686-688, 1983.
5. Wall, P. D.: The prevention of postoperative pain. Pain, 33: 289-290, 1988.
6. Coderre, T. J.; Vaccarino, A. L.; and Melzack, R.: Central nervous system plasticity in the tonic pain response to subcutaneous formalin injection. Brain Res., 535: 155-158, 1990.
7. Dickenson, A. H, and Sullivan, A. F.: Subcutaneous formalin-induced activity of dorsal horn neurones in the rat: differential response to an intrathecal opiate administered pre or post formalin. Pain,, 30: 349-360, 1987.
8. Woolf, C. J, and Wall, P. D.: Morphine-sensitive and morphine-insensitive actions of C-fibre input on the rat spinal cord. Neurosci. Lett., 64: 221-225, 1986.
9. Kissin, I.: Preemptive analgesia. Why its effect is not always obvious. Anesthesiology, 84: 1015-1019, 1996.
10. Kehlet, H, and Dahl, J. B.: The value of “multimodal” or “balanced analgesia” in postoperative pain treatment. Anesth. and Analg., 77: 1048-1056, 1993.
11. Highgenboten, C. L.; Jackson, A. W.; and Meske, N. B.: Arthroscopy of the knee. Ten-day pain profiles and corticosteroids. Am. J. Sports Med., 21: 503-506, 1993.
12. Dye, S. F.; Vaupel, G. L.; and Dye, C. C.: Conscious neurosensory mapping of the internal structures of the human knee without intraarticular anesthesia. Am. J. Sports Med., 26: 773-777, 1998.
13. Durand, A.; Richards, C. L.; and Malouin, F.: Strength recovery and muscle activation of the knee extensor and flexor muscles after arthroscopic meniscectomy. A pilot study. Clin. Orthop., 262: 210-226, 1991.
14. St.-Pierre, D. M.: Rehabilitation following arthroscopic meniscectomy. Sports Med., 10: 338-347, 1995.
15. Moffet, H.; Richards, C. L.; Malouin, F.; Bravo, G.; and Paradis, G.: Early and intensive physiotherapy accelerates recovery postarthroscopic meniscectomy: results of a randomized controlled study. Arch. Phys. Med. and Rehab, 75: 415-426, 1994.
16. Shelbourne, K. D, and Nitz, P.: Accelerated rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction. Am. J. Sports Med, 18: 292-299, 1990.
17. Rasmussen, S.; Larsen, A. S.; Thomsen, S. T.; and Kehlet, H.: Intra-articular glucocorticoid, bupivacaine and morphine reduces pain, inflammatory response and convalescence after arthroscopic meniscectomy. Pain,, 78: 131-134, 1998.
18. Moore, D. C.; Bridenbaugh, L. D.; Thompson, G. E.; Balfour, R. I.; and Horton, W. G.: Bupivacaine: a review of 11,080 cases. Anesth. and Analg, 57: 42-53, 1978.
19. Meinig, R. P.; Holtgrewe, J. L.; Wiedel, J. D.; Christie, D. B.; and Kestin, K. J.: Plasma bupivacaine levels following single dose instillation for arthroscopy. Am. J. Sports Med., 16: 295-300, 1988.
20. Nole, R.; Munson, N. M.; and Fulkerson, J. P.: Bupivacaine and saline effects on articular cartilage. Arthroscopy, 1: 123-127, 1985.
21. Henderson, R. C.; Campion, E. R.; DeMasi, R. A.; and Taft, T. N.: Postarthroscopy analgesia with bupivacaine. A prospective, randomized, blinded evaluation. Am. J. Sports Med., 18: 614-617, 1990.
22. Milligan, K. A.; Mowbray, M. J.; Mulrooney, L.; and Standen, P. J.: Intra-articular bupivacaine for pain relief after arthroscopic surgery of the knee joint in daycase patients. Anaesthesia,, 43: 563-564, 1988.
23. Chirwa, S. S.; MacLeod, B. A.; and Day, B.: Intraarticular bupivacaine (Marcaine) after arthroscopic meniscectomy: a randomized double-blind controlled study. Arthroscopy, 5: 33-35, 1989.
24. Geutjens, G, and Hambidge, J. E.: Analgesic effects of intraarticular bupivacaine after day-case arthroscopy. Arthroscopy, 10: 299-300, 1994.
25. Smith, I.; Van Hemelrijck, J.; White, P. F.; and Shively, R.: Effects of local anesthesia on recovery after outpatient arthroscopy. Anesth. and Analg, 73: 536-539, 1991.
26. Levine, J. D., and Taiwo, Y. O.: Involvement of the mu-opiate receptor in peripheral analgesia. Neuroscience, 32: 571-575, 1989.
27. Lawrence, A. J.; Joshi, G. P.; Michalkiewicz, A.; Blunnie, W. P.; and Moriarty, D. C.: Evidence for analgesia mediated by peripheral opioid receptors in inflamed synovial tissue. European J. Clin. Pharmacol., 43: 351-355, 1992.
28. Stein, C.; Millan, M. J.; Shippenberg, T. S.; Peter, K.; and Hertz, A.: Peripheral opioid receptors mediating antinociception in inflammation. Evidence for involvement of mu, delta and kappa receptors. J. Pharmacol. and Exper. Ther., 248: 1269-1275, 1989.
29. Stein, C.: The control of pain in peripheral tissue by opioids. New England J. Med., 332: 1685-1690, 1995.
30. Stein, C.: Peripheral mechanisms of opioid analgesia. Anesth. and Analg., 76: 182-191, 1993.
31. Stein, C., and Yassouridis, A.: Peripheral morphine analgesia. Pain,, 71: 119-121, 1997.
32. Stein, C.; Comisel, K.; Haimerl, E.; Yassouridis, A.; Lehrberger, K.; Herz, A.; and Peter, K.: Analgesic effect of intraarticular morphine after arthroscopic knee surgery. New England J. Med., 325: 1123-1126, 1991
33. Boden, B. P.; Fassler, S.; Cooper, S.; Marchetto, P. A.; and Moyer, R. A.: Analgesic effect of intraarticular morphine, bupivacaine, and morphine/bupivacaine after arthroscopic knee surgery. Arthroscopy, 10: 104-107, 1994.
34. Cepeda, M. S.; Uribe, C.; Betancourt, J.; Rugeles, J.; and Carr, D. B.: Pain relief after knee arthroscopy: intra-articular morphine, intra-articular bupivacaine, or subcutaneous morphine?. Reg. Anesth., 22: 233-238, 1997.
35. Reuben, S. S, and Connelly, N. R.: Postarthroscopic meniscus repair analgesia with intraarticular ketorolac or morphine. Anesth. and Analg., 82: 1036-1039, 1996.
36. Dalsgaard, J.; Felsby, S.; Juelsgaard, P.; and Froekjaer, J.: Low-dose intra-articular morphine analgesia in day case knee arthroscopy: a randomized double-blinded prospective study. Pain, 56: 151-154, 1994.
37. Heine, M. F.; Tillet, E. D.; Tsueda, K.; Loyd, G. E.; Schroeder, J. A.; Vogel, R. L.; and Yli-Hankala, A.: Intra-articular morphine after arthroscopic knee operation. British J. Anaesth., 73: 413-415, 1994.
38. Jaureguito, J. W.; Wilcox, J. F.; Cohn, S. J.; Thisted, R. A.; and Reider, B.: A comparison of intraarticular morphine and bupivacaine for pain control after outpatient knee arthroscopy. A prospective, randomized, double-blinded study. Am. J. Sports Med., 23: 350-353, 1995.
39. Aasbo, V.; Raeder, J. C.; Grogaard, B.; and Roise, O.: No additional analgesic effect of intra-articular morphine or bupivacaine compared with placebo after elective knee arthroscopy. Acta Anaesth. Scandinavica, 40: 585-588, 1996.
40. Björnsson, A.; Gupta, A.; Vegfors, M.; Lennmarken, C.; and Sjöberg, F.: Intraarticular morphine for postoperative analgesia following knee arthroscopy. Reg. Anesth., 19: 104-108, 1994.
41. Dierking, G. W.; Ostergaard, H. T.; Dissing, C. K.; Kristensen, J. E.; and Dahl, J. B.: Analgesic effect of intra-articular morphine after arthroscopic meniscectomy. Anaesthesia, 49: 627-629, 1994.
42. Rutberg, H.; Hakanson, E.; Anderberg, B.; Jorfeldt, L.; Martensson, J.; and Schildt, B.: Effects of extradural administration of morphine, or bupivacaine, on the endocrine response to upper abdominal surgery. British J. Anaesth, 56: 233-238, 1984.
43. Katz, J.; Clairoux, M.; Kavanagh, B. P.; Roger, S.; Nierenberg, H.; Redahan, C.; and Sandler, A. N.: Pre-emptive lumbar epidural anaesthesia reduces postoperative pain and patient-controlled morphine consumption after lower abdominal surgery. Pain,, 59: 395-403, 1994.
44. McQuay, H. J.; Carroll, D.; and Moore, R. A.: Postoperative orthopaedic pain - the effect of opiate premedication and local anesthetic blocks. Pain,, 33: 291-295, 1988.
45. Katz, J.; Clairoux, M.; Kavanagh, B. P.; Roger, S.; Nierenberg, H.; Redahan, C.; and Sandler, A. N.: Pre-emptive lumbar epidural anaesthesia reduces postoperative pain and patient-controlled morphine consumption after lower abdominal surgery. Pain,, 59: 395-403, 1994.
46. Whitford, A.; Healy, M.; Joshi, G. P.; McCarroll, S. M.; and O’Brien, T. M.: The effect of tourniquet release time on the analgesic efficacy of intraarticular morphine after arthroscopic knee surgery. Anesth. and Analg., 84: 791-793, 1997.
47. Denti, M.; Randelli, P.; Bigoni, M.; Vitale, G.; Marino, M. R.; and Fraschini, N.: Pre- and postoperative intra-articular analgesia for arthroscopic surgery of the knee and arthroscopic-assisted anterior cruciate ligament reconstruction. A double-blind randomized prospective study. Knee Surg Sports Traumat. Arthrosc., 5: 206-212, 1997.
48. El-Mansouri, M.; Reuben, S. S.; Sklar, J.; Gibson, C.; and Maciolek, H.: Preemptive analgesic effect of intraarticular morphine for arthroscopic knee surgery. Anesthesiology, 91: 953, 1999.
49. Smith, I.; Shively, R. A.; and White, P. F.: Effects of ketorolac and bupivacaine on recovery after outpatient arthroscopy. Anesth. and Analg., 75: 208-212, 1992.
50. Reuben, S. S, and Connelly, N. R.: Postoperative analgesia for outpatient arthroscopic knee surgery with intraarticular bupivacaine and ketorolac. Anesth. and Analg., 80: 1154-1157, 1995
51. Finnegan, M. A.: Off-label use of ketorolac. Anesth. and Analg., 83: 197, 1996.
52. Wilkinson, D. J.: Intraarticular ketorolac. Anesth. and Analg., 82: 433, 1996.
53. Ball, H. T.; Moore, J.; and Treadwell, B. V.: Ketorolac injectable NSAID effect on in vitro bovine cartilage degradation. Trans. Orthop. Res. Soc., 18: 726, 1993.
54. Reuben, S. S, and Connelly, N. R.: Postarthroscopic meniscus repair analgesia with intraarticular ketorolac or morphine. Anesth. and Analg., 82: 1036-1039, 1996.
55. Wang, J. J.; Ho, S. T.; Lee, S. C.; Tang, J. J.; and Liaw, W. J.: Intraarticular triamcinolone acetonide for pain control after arthroscopic knee surgery. Anesth. and Analg., 87: 1113-1116, 1998.
56. Gray, R. G.; Tenenbaum, J.; and Gottlieb, N. L.: Local corticosteroid injection treatment in rheumatic disorders. Sem. Arthrit. and Rheumat., 10: 231-254, 1981.
57. Grillet, B, and Dequeker, J.: Intra-articular steroid injection. A risk-benefit assessment. Drug Safety, 5: 205-211, 1990.
58. Gentili, M.; Juhel, A.; and Bonnet, F.: Peripheral analgesic effect of intra-articular clonidine. Pain, 64: 593-596, 1996.
59. Joshi, W.; Reuben, S. S.; Kilaru, P. R.; Sklar, J.; and Maciolek, H.: Postoperative analgesia for outpatient arthroscopic knee surgery with intraarticular clonidine and/or morphine. Anesth. and Analg., 90: 1102-1106, 2000.
60. Reuben, S. S, and Connelly, N. R.: Postoperative analgesia for outpatient arthroscopic knee surgery with intraarticular clonidine. Anesth. and Analg., 88: 729-733, 1999.
61. Gaumann, D. M.; Brunet, P. C.; and Jirounek, P.: Clonidine enhances the effects of lidocaine on C-fiber action potential. Anesth. and Analg., 74: 719-725, 1992.
62. Butterworth, J. F V, and Strichartz, G. R.: The alpha 2-adrenergic agonists clonidine and guanfacine produce tonic and phasic block of conduction in rat sciatic nerve fibers. Anesth. and Analg., 76: 295-301, 1993.
63. Nakamura, M, and Ferreira, S. H.: Peripheral analgesic action of clonidine: mediation by release of endogenous enkephalin-like substances. European J. Pharmacol, 146: 223-228, 1988.
64. Joshi, W.; Reuben, S. S.; Kilaru, P. R.; Sklar, J.; and Maciolek, H.: Postoperative analgesia for outpatient arthroscopic knee surgery with intraarticular clonidine and/or morphine. Anesth. and Analg., 90: 1102-1106, 2000.